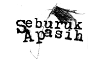Batu-batu yang Menghadap Kiblatnya

Yurnita buru-buru membersihkan tanah di telapak tangannya untuk menerima sodoran tangan saya. Darah Limapuluh Kota begitu kental di ujung bibirnya, saat saya dengar nada dari kalimat pertama yang diucapkan wanita lokal tersebut. Saya daratkan pantat ke atas rerumputan dan duduk di sampingnya. Dan, anak kecil yang sedang memanjat-manjat batu di depan kami jelas adalah cucu dari perempuan berumur lebih setengah abad di samping saya.
Siang nan nyalang, matahari seakan berkuasa menyinari padang hamparan batu di depan kami. Jangan ditanya betapa mengesankannya perjalanan menuju situs menhir Bawah Parit di Kenagarian Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota ini. Seorang kawan Melayu yang sebelumnya antusias saat saya ajak turut ikut riset kecil-kecilan, kini jelas tampak keruh air mukanya. Walaupun, sedikit terobati setelah gugusan menhir nyata di depan matanya, yang sebelumnya hanya ia lihat dalam bentuk foto di internet.
Perjalanan kami dari Ibu Kota Provinsi–Kota Padang–memakan waktu kurang lebih tujuh jam, jika roda motor terus berputar tanpa istirahat. Jalan putus di Silayiang Bawah yang belum selesai dibenahi mengharuskan kami mengambil jalan alternatif ke Malalak. Pada Bulan Mei lalu, air sungai serta merta meluluhlantakkan jalan raya beraspal, serta bangunan-bangunan angkuh yang berdiri mengangkangi jalur arus sungai. Bak air kembali mengambil jalannya.
Alfarizi angkat tangan saat kami berhasil tiba di Kota Payakumbuh, setelah kami berhasil melewati kemacetan, langit yang kadang hujan-kadang panas, hingga motor kami dua kali hampir beradu kambing dengan bus lintas sumatra yang–merasa dirinya motor supra-x–menyalip-nyalip kemacetan. Sebab kasihan dengan kawan Melayu itu, saya putuskan untuk bermalam di kampung Mama, Aia Tabik. Kami lanjutkan petualangan esok pagi. Lagipula, matahari sudah pulang ke Barat.

Masa kelam, kajayaan, pahit, dan manis bercampur satu meningalkan berbagai cerita dan kenangan yang akan terus bergulir dan tak terpecahkan dalam sejarah. Setidaknya, itulah yang saya temukan kala menginjakkan kaki di Nagari Maek. Kami harus melewati Taeh, Limbanang, Andiang, Banja loweh, dan Simun untuk menemukan harta karun di pelosok Sumatera Barat. Jalan sempit berliku memaksa kami berlaju pelan dan menikmati setiap tikungan.
Ada 374 menhir yang berdiri dan rebah di kawasan Cagar Budaya Bawah Parit. Saya gunakan ‘sekitar’ merujuk kata Yurnita, lagipula tidak ada nafsu saya untuk menghitung menhir itu satu persatu. Batu menhir terbesar di kawasan tersebut dulunya menjulang setinggi 405 cm, namun kini dalam posisi rebah. Sedangkan, menhir tertinggi yang masih tegak saat ini memiliki tinggi 326 cm.
Beberapa menhir memiliki ukiran, ada di pangkal, ada pula di pucuk. Ukiran dominan yang hampir ada di setiap menhir adalah motif kaluak paku. Dalam tulisannya, Lutfi Yondri (2014) menuliskan bahwa batu-batu tersebut terbuat dari batu andesit. Namun, masyarakat sekitar tak ambil susah menyebutkan batu-batu itu diambil dari Batang Maek. Aliran sungai di lereng bawahnya.
Saat remaja, Yurnita adalah salah satu saksi mata penggalian situs Bawah Parit oleh para arkeolog. Badan kecil belianya kala itu membuatnya tidak bisa melihat dari dekat proses penggalian.
“Itu penelitian keceknyo, Nak. Kami intik-intik sajo dari jouah. Tu basuo kerangka, model awak juo. Sagodang awak, lobiah-lobiah saketek. Tapi kapalonyo agak panjang ka lakang,” ujarnya antusias bak bercerita pada cucunya sendiri.
Di tengah padang menhir nan terik dia ceritakan apa yang didengar dan dilihat. Saya semakin bersemagat saat mendegar bahwa di bawah satu menhir ditemukan satu, empat, hingga paling banyak sembilan kerangka manusia.
“Berarti yang saya baca di buku pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) itu tidak akurat, Buk? Dulu saya belajar kalau menhir itu adalah sarana pemujaan ke arwah-arwah nenek moyang. Kepercayaan Dinanisme.”
“Itu kuburan,” jawabnya singkat. Tanpa data-data seperti arkeolog.
Menhir yang tegak dan rebah di situs Bawah Parit mengundang saya untuk menjelajahi jejak sejarah yang memesona. Tersembunyi dalam lindungan alam, menhir ini tidak hanya mencerminkan keahlian teknis yang luar biasa dari masa lampau, tetapi juga menimbulkan rasa kagum terhadap kebijaksanaan dan ketekunan para pembuatnya.
***

Di hari kedua, saya dan Alfarizi ingin mencari menhir-menhir yang menyatu dengan masyarakat. Sebab, kepala kami hanya ada satu pertanyaan. Apakah menhir masih bersama kehidupan, layaknya dulu sebagai penanda akhir sebuah kehidupan?
Hasrat demikian timbul sebab di beberapa situs menhir seakan berkumpul seperti kuburan masal yang sekelilingnya dipagar besi.
Kami menemukan puluhan menhir acak di sisi jalan aspal sempit.
Pagi itu kami niatkan untuk mencari kopi pagi setibanya di Koto Tinggi. Amunisi atau bensin sebelum berpetualang, begitu istilah kami. Koto Tinggi tidak lepas dari tancapan menhir. Bedanya, di sini menhir tidak berkumpul di satu titik saja. Berserak-serak. Ada yang di tengah pasar, depan Kantor Wali Nagari, sekolah, hingga masjid. Batu-batu tersebut seolah benar-benar difungsikan oleh manusia. Buktinya, kami tak sengaja menginjak menhir yang dijadikan gundukan tangga menuju sebuah kedai kopi.
“Matilah! Kena kutuk kita, Bang!” Alfarizi menepuk jidatnya, dan tertawa.
Namun, beberapa saat kemudian pelanggan kedai terlihat keluar-masuk tanpa menganggap batu tangga tersebut adalah sesuatu yang sakral. Saya bertanya di mana saja saya bisa menemukan menhir lainnya di sana pada anak muda yang sedang mengisap rokok kretek di kedai kopi.
“Bang bisa ketemu menhir kalau nanti salat Zuhur di masjid belakang,” ucapnya sembari menunjuk dengan mulut berasap.
“tapi, kalau mau lihat sekarang, di dekat sini ada bukit kecil. Banyak menhir di semak-semak sana sudah tertutup ilalang tinggi.”
Kami beranjak dari kursi kedai, membayar kopi, dan mengikuti langkah Rifki. Selama diperjalanan, dia bercerita kalau di bawah tanah yang kami pijak sekarang tertimbun puluhan menhir. Batu-batu itu lenyap bersama cor, beton, dan aspal. Mereka bingung mau diapakan dan dipindahkan ke mana. Masyarakat Koto Tinggi dahulunya kurang sosialisasi mengenai batu-batu yang berserakan di halaman rumah mereka.
Sesekali menhir yang sama tinggi dengan mata kaki mencuri pandangan saya. Batu tersebut menyatu bersama semen cor sebuah ruko toko kelontong. Selain itu, saya juga terperangah melihat menhir yang pucuknya terikat tali tambang, hingga berfungsi sebagai pengikat tali jemuran.
Menhir di sini tidak sesakral yang lainnya di situs. Mereka lebur begitu saja bersama kehidupan. Ibarat tanaman liar yang tidak bisa ditebang.
Rokok kretek saya habis ketika sampai di tujuan. Desau angin membuatnya lebih cepat terbakar dari seharusnya. Sorak-sorai anak-anak bermain sepak bola menemani percakapan kami. Rifki menyibak tanaman liar di pangkal sebuah pohon pisang dan seonggok menhir pun tampak. Tinggi sepinggang Alfarizi, sekitar satu meter. Berdirinya sudah agak condong ke utara, sepertinya itu pengaruh dari tanah yang lunak. Di belakang, terhampar beberapa tabek ikan milik warga setempat.
Kami menemukan beberapa kesamaan ukiran dengan batu di situs Bawah Parit. Motif kaluak paku selalu ada di setiap pucuk. Saya mengira manusia zaman dahulu suka terinspirasi dengan motif alamiah, yang mana tumbuhan pakis (paku dalam bahasa setempat) bebas tumbuh liar di penjuru Maek.
Ke bawah sedikit, saya menemukan dua batu besar yang rebah.
“Ini juga menhir?” tanya saya ke Rifki yang merespon dengan wajah kebingungan.
“Indak sepertinya, Bang. Tapi coba Bang lihat, ‘kan Bang mahasiswa.” Dia meyakini ‘kemahasiswaan’ saya cukup untuk memindai sebuah batu yang umurnya melebihi Christoper Colombus si penemu benua.
Saya menemukan beberapa ukiran pudar setelah membalikkan batu tersebut. Bahkan, setiap pangkalnya seperti saling melengkapi jika disatukan. Hipotesis saya kedua batu tersebut adalah satu batu yang telah patah, lalu dibiarkan saja tergeletak.
Keberadaan menhir di Maek meyakinkan warga lokal bahwa asal muasal orang Minang adalah dari Maek, ke Payakumbuh, lalu ke Paringan. Kebanggaan tersendiri bagi mereka yang menyadari bahwa negerinyalah paling tua. Anggapan ini melawan catatan-catatan populer yang mana meyakini asal muasal orang Minang dari Paringan. Entah yang mana yang betul, saya hanya tersenyum.
Muazin telah mengumandangkan azan, pertanda waktu Zuhur telah masuk. Saya teringat batu-batu di masjid yang diceritakan Rifki.
Menhir-menhir itu letaknya mengitari masjid ibarat pagar, bahkan warga tidak berani memindahkannya saat membuat pagar semen. Kata salah satu jamaah, biarlah batu itu berdiri sebagaimana dahulunya.
Menhir di Koto Tinggi tidak sekadar menjadi peninggalan sejarah yang berdiri megah, tetapi telah menyatu erat dengan kehidupan masyarakat setempat. Di tengah hamparan sawah dan pegunungan yang menakjubkan, menhir ini menjadi sebuah kebanggan sosial.
Dalam kejayaannya yang megah, menhir ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda temporal yang monumental tetapi juga sebagai penghormatan spiritual terhadap kekuatan alam yang dianggap suci oleh masyarakat setempat. Dalam pandangan warga, menhir ini bukan sekadar objek fisik, tetapi representasi dari koneksi mendalam antara manusia dan alam semesta, yang terwujud dalam ritual dan cerita-cerita yang turun-temurun.
***
Mengunjungi situs menhir di Maek memancarkan nuansa refleksi yang mendalam. Dalam bising deru motor, saya merenungkan keajaiban arsitektur prasejarah yang saya saksikan, mengingat momen ketika saya berdiri di antara monumen-monumen megah yang menyimpan misteri masa lalu.
Kami berhenti sejenak di SPBU Ngalau untuk mengisi penuh tangki bensin dan membeli air dingin dari minimarket. Tiba-tiba sesuatu menyentak pikiran saya yang ingin membuktikan isu bahwa menhir-menhir itu menghadap ke Gunung Sago.
Gunung di wilayah Payakumbuh tersebut masuk akal jika dikatakan tempat tertinggi dari wilayah sekitarnya. Beberapa bacaan saya mengatakan alasan menhir-menhir menghadap Gunung Sago karena itulah puncak tertinggi. Dan, mereka berasumsi kalau manusia dahulu meyakini setiap arwah yang dikubur akan melayang ke ketinggian, seperti sebuah gunung. Namun, siapa yang bisa tahu isi keyakinan hati seseorang? Apalagi manusia yang terpaut jarak 3000 tahun sebelum masehi.
Setelah beberapa saat menatapi google maps di ponsel, saya menemukan beberapa kebenaran dari anggapan di atas. Walaupun, ada beberapa menhir yang kemungkinan berubah letaknya, lekukan pucuknya tidak menghadap Gunung Sago.
Perjalanan pulang kami ditemani rekaman-rekaman petualangan yang penuh dengan batu.
***
Johan Arda, penulis “Ritual Malam Minggu”. Emerging Writer di Balige Writers Festival 2023, Toba, Sumatra Utara.