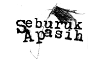Cerpen Adriansyah Subekti: Anekdot Labirin Penderitaan
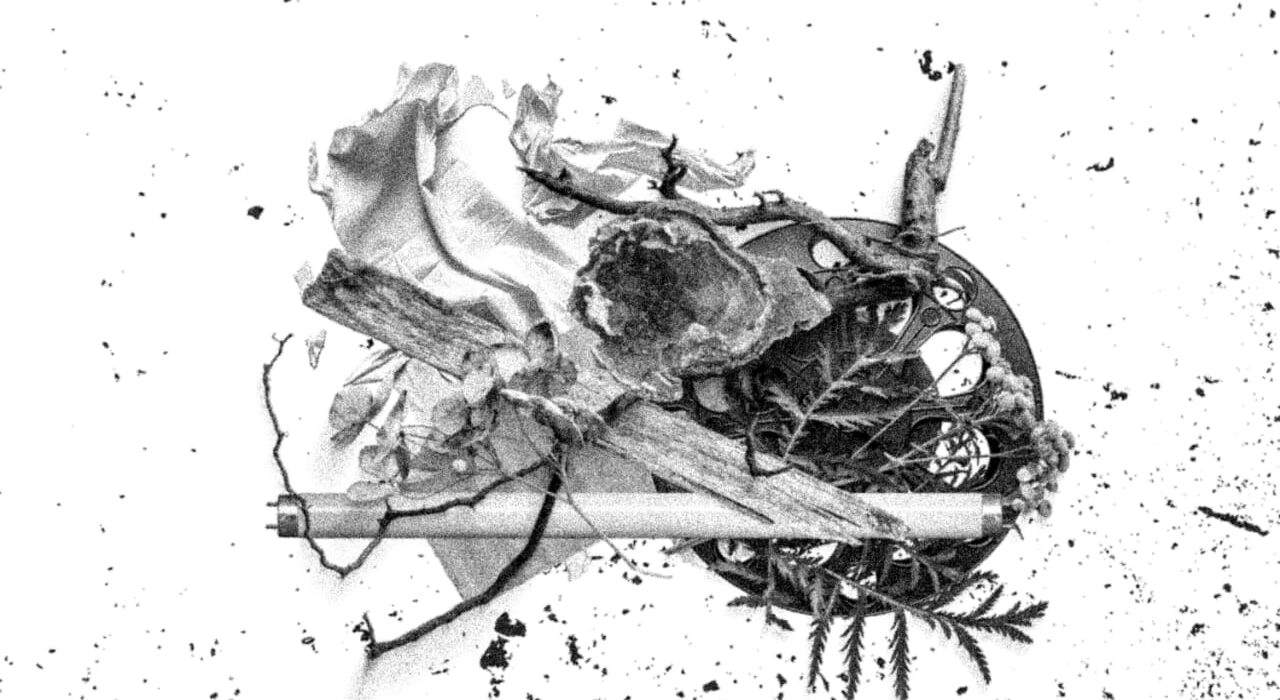
Malam ini adalah malam paling busuk bagiku. Ingin sekali kulontarkan semua kata-kata kotor kepada langit malam yang kopong. Tetapi kata-kataku seakan tertindih batu besar di dadaku. Ia hancur berkeping-keping seperti botol bir yang mencium keras trotoar. Dan aku hanya bisa berteriak dalam batin. Asu!
Tatkala sore berwajah mendung, sebelum malam datang dan membusuk, istriku memeluk tubuhku dan mencium bibirku selama tiga ratus detik dengan penuh gairah. Itu adalah pelukan dan ciuman terakhirku dengannya sebelum segalanya menjadi tai. Sebelum ia berpamitan dengan alasan ingin menghadiri rapat dadakan di kantornya. Sebelum ia berbohong kepadaku seperti orang tua kepada anaknya. Sebelum ia ketahuan melakukan seks anjing di atas meja kantor dengan bosnya yang bajingan. Ia mengkhianatiku. Dan aku benci pengkhianatan.
Sejak kejadian itu, dunia porak-poranda seketika tumbuh di kepalaku. Dunia di kepalaku berisi kebakaran-kebakaran, teriakan-teriakan, gempa maha dahsyat, hujan batu, gedung-gedung hancur, dan seorang anak kecil yang menangis di sudut paling gelap. Sendirian.
Malam ini, di jembatan underpass beraroma pesing, aku cuma ingin menghabiskan malam dengan mabuk ciu dan bengong seorang diri. Memandangi wajah langit yang juga memandangku. Aku dan langit berwajah sama. Sama-sama berwajah kopong juga pucat. Seperti badut yang ingin mati.
Gegas kusobek ujung plastik ciu dengan gigi taringku serupa vampir yang kehausan darah. Tetapi asu! Tiba-tiba nada dering ponselku berteriak seperti teriakan orang kesurupan. Sekejap kuarahkan pandang ke layar ponsel. Adikku mengirimi pesan. Ia mengabarkan kalau penyakit asma Ibu kambuh, dan Ibu baru saja dibawa ke rumah sakit.
Mendadak dadaku sesak sekali. Tubuhku seperti bom bunuh diri yang tinggal menunggu saatnya meledak. Dengan penuh putus asa kulemparkan plastik ciu itu ke sembarang arah. Aku tak jadi mabuk ciu malam ini. Aku segera bergegas ke rumah sakit untuk menemui Ibu. Sedang malam semakin busuk belaka.
Di rumah sakit, Adik sudah menangis tanpa suara di kursi kayu lapuk. Di bawah lampu neon yang sekarat. Dadaku masih sesak. Perasaan-perasaan ganjil memenuhi batok kepalaku yang porak-poranda.
“Di mana Ibu?” tanyaku kepada Adik yang menangis dan menangis. Tak ada jawaban. Dadaku semakin sesak. Aku tak bisa menangis. Tidak, aku tidak boleh menangis. Kuulangi pertanyaanku kepada Adik, masih tak ada jawaban. Aku frustrasi. Segera aku masuk ke ruang perawatan pasien. Kutengok satu-persatu orang sakit di ruangan itu. Semuanya asing. Yang kulihat hanya wajah-wajah pucat sengsara dan beraroma tanah. Tak kutemui wajah Ibu.
Di mana Ibu? Aku bertanya-tanya.
Aku lantas keluar ruangan dan duduk di sebelah Adik yang masih menangis. Kami berdua diam saja. Adik menangis tanpa suara. Aku cuma melamun dan menarik napas dalam-dalam. Pikiranku terasa kosong sekaligus penuh.
“Ibu sudah tidak ada, Mas. Ibu sudah dibawa ke kamar mayat. Tinggal dipulangkan. Menunggu mobil ambulans.”
Ibu mati. Di kamar mayat. Tinggal dipulangkan. Menunggu ambulans. Begitulah kata Adik.
Mendadak ponselku berteriak. Aku merasa geram karenanya. Di tengah kecamuk kekacauanku, kusempatkan memandang layar ponselku. Istriku meneleponku dan mengirimi beberapa pesan. Ia marah kepadaku lantaran aku tak berada di rumah dini hari begini. Ia menuduh aku sedang mengapeli tlembuk di warung remang-remang penjual obat kuat. Tolol.
Kubanting ponselku ke lantai rumah sakit saat itu juga dengan penuh amarah. Aku tak peduli. Dadaku sesak. Aku lantas berlari menuju kamar mayat. Sempoyongan menanggung kecamuk kekacauan di dada. Kupaksa petugas untuk membukakan pintu kamar mayat. Aku ingin melihat mayat Ibu. Mayat Ibu. Mayat yang baru saja dicabut nyawanya.
“Lima menit saja, Mas!” tegas petugas rumah sakit kepadaku. Aku mengangguk dan meminta kepadanya supaya aku dibiarkan sendirian di kamar mayat. Tak perlu ditemani. Aku tak butuh teman. Si petugas mengiyakan permintaanku.
Memasuki kamar mayat, hawa dingin dan bau busuk amis menyelimuti sekujur tubuhku. Mendadak aku sedikit kaku. Kupaksakan langkahku mengitari mayat-mayat yang diselimuti kafan putih. Menikmati suasana ganjil kamar mayat. Kehidupan terasa punah di kamar mayat.
Sesaat aku menerka-nerka mayat Ibu. Aku menghampiri mayat yang paling dekat dengan pintu keluar. Kusibak kafan putih mayat itu. Kulihat wajah pucat Ibu yang tersenyum. Aku balik tersenyum kepadanya. Tiba-tiba kudapati air menetes tiga kali di kafan putih. Tanpa kusadari, cekung mataku meneteskan air mata. Aku menangis. Dan wajahku terasa panas.
“Selamat beristirahat, Bu. Setelah ini aku akan menggantikan peranmu untuk mengurus Adik. Nasib kita tak ada beda. Kau dikhianati suamimu yang bangsat. Aku juga dikhianati istriku. Selamat jalan,” bisikku lirih di hadapan wajah Ibu yang pucat amis.
Aku mencium kening Ibu untuk terakhir kalinya. Dingin. Lantas kututup kembali wajah Ibu dengan kafan putih seperti semula.
Kurenungkan hidupku yang seperti tai. Penderitaanku datang berturut-turut seperti hujan meteor di film-film distopia. Diriku hancur lebur. Pesakitan. Aku sudah kalah dalam lomba mengejar kehidupan ideal. Segalanya runtuh sudah. Hidupku busuk belaka.
Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Waktuku di kamar mayat sudah habis. Seorang petugas menyuruhku untuk keluar. Aku keluar dengan tubuh serupa mayat yang berjalan. Dingin, pucat, dan kaku.
Esoknya, mayat Ibu sudah selesai dikubur di kuburan Watu Kuning. Tak banyak orang ikut mengantar pemakaman Ibu sebab hari itu hujan begitu besar dan petir-petir menggelegar. Aku membaca pertanda cuaca hari itu bahwa Tuhan sedang menyambut kematian Ibu dengan hujan dan petir. Barangkali di atas langit sana, di surga, Tuhan sedang melakukan semacam karnaval untuk menyambut satu hambanya yang paling sabar di dunia. Ibu.
Hari-hari setelah kematian Ibu, aku dan Adik sudah mulai berdamai dengan keadaan. Aku mulai tinggal berdua saja bersama Adik. Adikku perempuan. Ia masih SMA. Cerdas. Kecerdasannya membawanya mendapatkan beasiswa di sekolahnya. Jadi aku tak perlu repot memikirkan biaya untuk sekolahnya. Adik juga piawai mencari uang saku sendiri dengan berjualan manik-manik warna-warni yang ia buat menjadi kalung, gelang, dan cincin. Ia menjadi anak perempuan yang mandiri sejak bapaknya yang tak tahu diri itu minggat meninggalkannya.
Aku berharap ia menjadi perempuan yang memiliki masa depan cerah. Tak seperti aku yang mengidap depresi akut dan bolak-balik menclok ke ruang psikiater. Pesakitan. Tubuhku adalah peti kosong yang menampung jutaan obat anti-depresan.
Selanjutnya, Adik memberitahuku bahwa hari besok, ia akan menginap tiga hari dua malam di sekolahnya. Mengikuti kegiatan pramuka, katanya. Aku percaya saja kepadanya lantaran Adik tak pernah membohongiku. Semua itu terbukti setelah aku mengantarnya ke gerbang sekolah dan banyak siswa-siswa yang mengenakan seragam pramuka lengkap.
“Jaga dirimu baik-baik. Jangan sungkan meminta pertolongan kepada orang lain,” ucapku kepada Adik di depan gerbang sekolah sore itu. Ia mengangguk lantas mencium tanganku.
Menunggu malam, sore itu kuputuskan untuk memutari kota seorang diri. Menikmati pemandangan orang-orang kota yang sibuk dan lelah. Sinar matahari masih menyengat di kulitku yang coklat. Melihat langit sore berwarna jingga, pikiranku berlari menuju masa-masa di mana aku dan istriku menghabiskan sore di alun-alun kota. Dan entah kenapa, aku memutuskan berhenti di alun-alun kota. Duduk di kursi taman yang tersedia. Melamuni momen-momen bahagia yang cepat lenyap. Serupa butir debu trotoar tersapu angin. Cintaku telah mendingin.
Saat aku duduk di kursi taman alun-alun sambil memandang jalanan kota yang berisik, mendadak aku melihat istriku sedang tertawa di atas motor N-max bersama seorang lelaki tua lalu lenyap dari pandanganku dalam sekejap.
Melihat kejadian itu, aku merasa mati suri di kursi taman ini. Tatapanku kosong melompong. Dadaku keras batu. Dan wajahku panas neraka.
Malam ini, di pinggir rel beraroma pesing, aku cuma ingin menghabiskan malam dengan mabuk ciu dan bengong seorang diri. Memandangi wajah langit yang juga memandangku. Aku dan langit berwajah sama. Sama-sama berwajah kopong juga pucat. Seperti badut yang ingin mati.
Gegas kusobek ujung plastik ciu dengan gigi taringku serupa vampir yang kehausan darah. Tetapi asu! Tiba-tiba nada dering ponselku berteriak seperti teriakan orang kesurupan. Sekejap kuarahkan pandang ke layar ponsel. Sebuah nomor tak dikenal mengirimi pesan kepadaku.
Kubaca pesan anonim itu sembari menenggak ciu tiga kali tegukan. Mendadak pikiranku nanar saat membaca pesan itu. Dadaku sesak. Wajahku panas neraka. Aku menangis tanpa sadar.
Pesan itu mengabarkan bahwa Adik telah diperkosa oleh seorang teman laki-lakinya di toilet sekolah. Kabarnya, keadaan Adik saat ini masih linglung. Ia pasti mengalami trauma yang sangat dalam. Asu!
Aku sangat terpukul setelah mendengar kabar yang menimpa Adik malam ini. Kiamat seakan datang berkali-kali di sekujur tubuhku. Aku tak tahu apa yang mesti aku lakukan malam ini. Aku tak tahu apa yang mesti aku perbuat untuk hidupku yang neraka. Segalanya terasa buyar. Segalanya terasa runtuh dalam sekejap. Aku tak bisa memikirkan apa-apa lagi.
Sekarang, di pinggir rel berbau pesing ini, di bawah pucat langit malam, aku hanya menunggu sebuah kereta lewat. Aku ingin menaiki kereta. Kereta kematian. Aku ingin menaiki kereta kematian dan membusuk bersama malam.
Sembari menunggu kereta kematian, aku memutar sebuah lagu sedih milik The Strokes yang berjudul Selfless di ponselku.
Sesaat nada lagu menusuk lubang kupingku. Aku terbahak-bahak sambil berteriak mengikuti irama lirik lagu.
Can the dark side light my way? Oh yeah, yeah …
Mendadak kulihat sebuah kereta datang tak lama setelahnya. Suara klaksonnya menggelegar serupa sangkakala kiamat. Aku memandang tajam ke arah kereta itu. Aku ingin menaikinya. Menaiki kereta kematian.
Oh! Tetapi rupanya, ini bukan kereta kematian. Ini kereta api dengan ratusan penumpang di dalamnya. Sesekali kulihat wajah bocah melambai-lambai di balik kaca jendela kereta. Entah apa artinya.
Tiba-tiba, aku berubah menjadi badut yang ingin mati.
Dan menangis. Lalu tertawa.
Kalibogor, 2023
Adriansyah Subekti, penulis yang lahir dan besar di Purwokerto. Beberapa tulisannya pernah dimuat di media cetak maupun daring