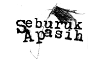Panggung di Balik Jeruji

Di bawah bayang-bayang pagar tinggi yang baru berdiri, Bara berdiri memandangi gerbang terkunci di depan gedung kesekretariatan. Dulu, tempat itu adalah ruang bagi teater ekspresif mereka. Tempat di mana setiap kata yang diucapkan dari naskah menjadi suara kebebasan. Sekarang, jeruji besi itu berdiri kokoh, membatasi bukan hanya fisik, tetapi juga mimpi dan kreativitas.
“Gila, kayak penjara,” keluh Aryo, sutradara teater mereka, sambil menyulut rokok yang ujungnya bergetar oleh amarah tertahan. “Mau latihan di mana kita sekarang?”
Bara diam. Matanya masih terpaku pada pagar tinggi yang terasa begitu mengintimidasi. Di balik jeruji, kursi-kursi berdebu dan panggung kayu yang biasa mereka pakai terlihat sunyi, seakan merindukan suara tawa dan tepuk tangan yang pernah menggema.
“Pakai taman kampus?” usul Fani, pemain utama yang terkenal dengan suara lantangnya. “Tapi… berisik.”
“Aula fakultas?” sambung Tama, anggota baru yang masih terlihat canggung.
“Udah dipesan untuk seminar. Lagian, izinnya ribet sekarang,” balas Aryo. “Dulu, tinggal ngomong sama sekuriti. Sekarang semua harus ada tanda tangan dekan.”
Keheningan menggantung di antara mereka. Bara bisa merasakan ketidakberdayaan yang menyelimuti timnya. Dia menggenggam naskah tebal yang sudah dipelajarinya selama berminggu-minggu. Kisah tentang perjuangan kebebasan yang ironisnya terhenti oleh pagar besi ini.
Namun, di saat matanya kembali tertuju pada jeruji yang dingin dan tak bernyawa itu, Bara melihat sesuatu yang berbeda. Pagar itu tinggi, namun tembus pandang. Seakan-akan ia menertawakan mereka yang terkurung, memperlihatkan apa yang tak bisa dijangkau namun tak sepenuhnya disembunyikan.
“Bagaimana kalau…” suara Bara pelan, namun penuh keyakinan. “Kita jadikan pagar ini panggung kita?”
Aryo menoleh, alisnya terangkat bingung. “Maksudnya?”
“Lihat, jarak antar jeruji itu cukup untuk kita menampilkan bayangan. Kalau kita pakai lampu sorot dari sini…” Bara menunjuk area luar pagar, “…kita bisa menampilkan siluet di dinding gedung. Kita bisa main bayangan.
”Mata Fani berbinar, menangkap ide gila yang ditawarkan Bara. “Teater bayangan… di balik jeruji?”
Bara mengangguk. “Jeruji ini bukan penghalang. Kita jadikan dia bagian dari cerita kita.”
Latihan dimulai dengan penuh semangat. Bara mengatur lampu sorot di berbagai sudut, mencoba berbagai posisi untuk menciptakan efek bayangan yang dramatis. Mereka bermain dengan siluet, menciptakan bentuk-bentuk simbolis yang memperkuat emosi dalam naskah. Gelak tawa dan teriakan antusias memenuhi area itu, seakan-akan jeruji besi tak pernah ada.
Namun, di tengah latihan, sesuatu yang ganjil terjadi. Saat Bara berdiri di depan lampu untuk menunjukkan adegan pelarian, bayangannya tampak lebih besar dari seharusnya. Bahkan ketika ia bergerak mundur, bayangan itu tetap pada posisinya.
“Eh, bentar deh, Bara nggak gerak, kan?” tanya Aryo dengan nada bingung.
Bara menggeleng. Semua mata kini terpaku pada bayangan yang terus bergerak, meski Bara sudah berdiri diam. Siluet itu tampak meronta, seakan berusaha keluar dari jeruji yang membatasi.
Fani melangkah mundur, merasakan bulu kuduknya meremang. “aku… aku rasa kita harus berhenti dulu.
”Namun Aryo menggeleng keras. “Justru ini yang kita cari! Efek bayangan yang nggak terduga. Ini bakal bikin penonton makin terkesan.”
Bara masih memperhatikan bayangan itu, matanya menyipit penuh rasa ingin tahu. “Tapi… kenapa bayangan itu bisa gerak sendiri?”
“Nggak penting. Yang penting ini keren!” Aryo mulai mengatur posisi lampu, mencoba menghasilkan efek yang lebih dramatis. “Lagian, kalian yakin nggak ada orang lain di balik pagar sana?”
Mereka saling berpandangan, mencoba mencari akal sehat di tengah keganjilan yang terjadi. Tama berjalan ke sisi pagar, mengintip ke sela-sela jeruji. “Nggak ada siapa-siapa. Cuma kursi-kursi tua dan panggung kosong.”
“Apa mungkin Cuma ilusi optik?” Fani mencoba berpikir logis, meski nada suaranya terdengar ragu.
“Terserah kalian mau nyebut apa. Yang jelas, ini bakal jadi pertunjukan teater yang nggak pernah dilihat orang sebelumnya!” Aryo semakin bersemangat, seolah-olah keganjilan itu hanyalah bagian dari keajaiban panggung.
Mereka melanjutkan latihan dengan waspada, sesekali melirik bayangan yang masih bergerak tanpa kendali. Meskipun ketakutan menghantui, antusiasme untuk menciptakan teater yang berbeda terus membakar semangat mereka.
Malam itu tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Dengan jantung berdebar, para pemain berkumpul di luar pagar, bersiap untuk menampilkan karya yang lahir dari kegelisahan mereka. Bara mengatur lampu sorot dengan hati-hati, memastikan setiap bayangan jatuh dengan sempurna di dinding gedung yang menjulang di balik jeruji.
Puluhan mahasiswa mulai berdatangan, penasaran dengan undangan misterius yang tersebar secara anonim. Mereka berdiri mengelilingi pagar, membentuk setengah lingkaran yang menyaksikan panggung tak biasa itu. Beberapa dari mereka berbisik, mencoba memahami apa yang akan disuguhkan oleh teater bayangan di balik jeruji besi ini.
Aryo mengambil alih arahan, suaranya tegas namun penuh emosi. “Ingat, ini bukan Cuma pertunjukan. Ini perlawanan. Suara kita nggak bisa dibungkam sama pagar setinggi apa pun.”
Fani mengangguk, menggenggam naskah dengan erat. Malam ini, dia bukan hanya memainkan peran seorang tahanan. Dia akan menjadi simbol bagi mereka yang terkurung oleh batas-batas yang tak terlihat.
Bara menyalakan lampu sorot pertama, memproyeksikan bayangan siluet Fani di dinding. Suasana hening seketika, penonton terpaku melihat bayangan yang bergerak anggun, mengisahkan kebebasan yang terenggut.
Pada adegan pertama, sang tahanan terlihat berdiri dengan kepala tertunduk, bayangannya membesar dan menyusut, seolah-olah dinding jeruji semakin menyempit. Ia mencoba berteriak, namun suara yang terdengar hanyalah gema kesunyian. Penonton terdiam, merasakan kesepian yang menyakitkan dari dalam kurungan tak terlihat.
Adegan berikutnya menampilkan siluet tangan yang meraih ke atas, berusaha menjangkau kebebasan yang tidak pernah terlihat. Bayangan itu melayang sejenak sebelum jatuh terkulai, melambangkan harapan yang hancur. Beberapa penonton terlihat mengusap air mata, larut dalam kepedihan yang terpancar dari bayangan di dinding.
Saat musik mulai mengalun pelan, bayangan sang tahanan berubah menjadi sosok kecil yang berjalan terhuyung-huyung, dikejar oleh bayangan besar yang melambangkan ketakutan dan kekuasaan. Sang tahanan berlari, mencoba menghindar, namun bayangan besar itu selalu mengikutinya, membentuk lingkaran jeruji yang semakin mengecil.
Di puncak emosi, bayangan sang tahanan jatuh berlutut, kedua tangan menggenggam jeruji bayangan yang tak terlihat. Ia mengguncang-guncang jeruji itu, mencoba melarikan diri dari batasan yang mengurungnya. Namun, semakin kuat ia melawan, semakin kuat pula bayangan jeruji itu mencengkeram tubuhnya.
Adegan-adegan tersebut mengantarkan cerita menuju klimaks yang penuh ketegangan, membuat penonton tercekat dalam keheningan yang mencekam.
Sebelum sampai ke adegan terakhir, pertunjukan itu menghadirkan serangkaian adegan yang penuh emosi. Bayangan para aktor bergerak dengan anggun, memainkan kisah tentang seorang tahanan yang kehilangan kebebasan. Setiap gerakan menciptakan simbol-simbol yang menggugah rasa gelisah di hati penonton.
Namun, saat sorot lampu terakhir padam, bayangan itu tampak bergerak, perlahan merangkak mendekati pagar. Saat adegan terakhir, siluet sang tahanan berdiri tegak di balik jeruji. Ia menatap ke arah penonton, lalu perlahan membuka tangannya seakan menyentuh jeruji. Bayangannya melebar, melampaui batas fisik pagar. Bayangan itu tetap berdiri di sana, menatap penonton. Mata penonton terpaku, tak percaya dengan apa yang dilihat. Beberapa mulai berbisik, kebingungan. Bayangan itu kemudian menggerakkan tangannya, seolah-olah berusaha menjangkau mereka, membuat suasana semakin mencekam.
Fani yang seharusnya memerankan sang tahanan keluar dari balik panggung, wajahnya pucat. “Bara… itu bukan aku. Aku nggak pernah berdiri di sana.”
Pagar itu bergetar pelan, seakan tertawa dalam diam. Bayangan itu tak lagi diam, perlahan merangkak, menjauhi panggung dan mendekati gerbang. Langkahnya berat, namun pasti, seolah-olah mencoba keluar dari penjara yang mengekangnya selama ini.
Penonton bergeming, tak satu pun yang berani bergerak. Bayangan itu meraih jeruji dengan jemari hitamnya yang memanjang, menembus batas fisik yang seharusnya tak bisa dilalui. Lamat-lamat terdengar suara rintihan, lirih namun menyayat.
Saat lampu benar-benar padam, jeritan melengking terdengar, bergema di antara dinding-dinding gedung yang kini terasa lebih sempit dari sebelumnya. Pagar itu diam, tak lagi bergetar. Namun sesuatu telah pergi, keluar dari balik jeruji, meninggalkan kesunyian yang menakutkan.
Pertunjukan usai, namun rasa gelisah tidak ikut menghilang. Penonton pergi dengan kepala penuh tanya, meninggalkan bayangan yang tak lagi terlihat, namun kehadirannya tetap terasa di udara malam yang dingin.
Pandu Aryo, mahasiswa Sastra Inggris Universitas Andalas lahir pada 17 Oktober 2003. Selain sibuk luliah, penulis juga aktif berkegiatan di UKMF Labor Penulisan Kreatif Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas