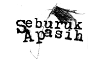Laut yang Tenang, Pantai yang Kacau

Pada akhir pekan yang padat. Ban motor saya menggelinding ke arah matahari tenggelam, untuk sejenak merehatkan kepala dari hiruk-pikuk dunia perkuliahan yang monoton. Dari ketinggian Kota Padang, saya harus menyelip sana-sini kendaraan para pekerja kantoran, sesekali terjebak macet yang untungnya tidak berlarut.
Ini tahun keempat saya di Kota Padang. Ibu Kota Provinsi yang sedang tertatih-tatih berjuang merangkak menuju kemajuan peradaban, seperti para tetangganya. Sebagai mahasiswa perantauan dari Lima Puluh Kota yang sejuk, hidup di Padang merupakan perjuangan melawan hawa panas udara pantai. Namun di balik itu, Padang juga patut dinikmati perlahan-lahan, seperti meneguk secangkir kopi pahit.

Foto: M. Fahrul
Pantai adalah salah satu–atau mungkin satu-satunya–tujuan wisata yang layak disombongkan oleh kota yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia tersebut. Dan mau tidak mau, paling tidak satu kali saja saya pernah mengunjunginya.
Pantai Padang atau acap disebut Taplau (Tapi Lauik= Tepi Laut) terbentang dari Utara ke Selatan, dari Purus hingga Muara Batang Arau. Ia menjadi hilir air. Di sanalah, para wisatawan banyak duit dari bermacam daerah bertamasya demi melihat hamparan air yang tidak berubah sejak zaman Portugis pertama kali menambatkan perahu mereka di Pantai Barat Sumatera.
Saya memarkirkan motor di samping masjid putih yang berdiri ciamik, menambah keindahan pemandangan. Belum selesai saya melepas pegait helm, seorang pria paruh baya berompi orange berlirih di belakang telinga saya, “Parkirnyo kini yo, Kak.” (Parkirnya sekarang ya, Kak.)
Sontak, saya menyerahkan selembar uang lima ribu rupiah tanpa mengeluarkan sepatah apapun. Lalu, sang juru parkir pergi begitu saja, tanpa memberikan kembalian uang.
“Oh, mungkin saya dipatok harga wisatawan,” benak saya.
Tanpa memusingkan uang kembalian yang saya anggap sebagai sedekah, saya beringsut menjatuhkan pantat ke atas gundukan batu penahan ombak. Kala mentari perlahan jatuh, banyak muda-mudi menghabiskan senja di sana. Bercengkrama hilir-mudik tanpa beban.
Selain tujuan wisata, di sepanjang perjalanan saya memahami bahwa Taplau juga tempat bergantung para pedagang kaki lima, mulai penjual kelapa muda, langkitang, karupuak leak, minuman dingin, tisu, mainan, kopi sachet hingga kopi cafe yang mahal, hingga penyewa motor mainan. Taplau seperti batang mangga yang memberi makan parasit yang hinggap di atasnya.
Para pedagang mendirikan tenda lusuh semi permanen mereka di sepanjang pedestrian dengan memancang tali temali ke batang kelapa terdekat. Mulai sejak matahari perlahan jatuh hingga larut malam, mereka berjuang dengan berharap ada satu dua pengunjung yang singgah, barang membeli dagangan mereka. Dan itu terus berulang setiap harinya, tanpa mengharapkan titik ‘kaya’. Yang penting bisa untuk makan besok.
Seiring perkembangan wisata Ibu Kota Provinsi ini, Pemerintah mulai berpikir bahwa Taplau harus dibenahi karena semrawut tenda pedagang yang merusak estetika penataan kota. Walaupun sudah menjanjikan tempat baru dengan dalih lebih tertata, para pejabat gendut tersebut tidak satu kali ricuh dengan para pedagang yang tidak terima lahannya digusur. Pernah sekali, sempat terjadi aksi lempar batu yang saling melukai satu sama lain.
“Lalu bagaimana seharusnya Taplau ditata, menurutmu?” tanya saya suatu ketika pada seorang teman.
“Melenyapkan tenda-tenda itu sama saja dengan memusnahkan para pribumi pesisir yang sudah dikenal keras kepala. Mau berapa kali dan dengan teknik pendekatan apapun, mereka tidak akan mundur barang satu langkah pun,”
“Lalu?”
“Soal solusi, itu tetap masih urusan pemerintah. Sudah, pertanyaanmu membuat saya pusing.”
Langit di Taplau selalu memamerkan kedamaian, tetapi ada jejak-jejak kelam yang tak terelakkan. Pasir-pasir yang menggulung lembut di bibir pantai, seolah berusaha menggenggam setiap kenangan yang terbawa ombak. Namun, tak ada yang bisa menahan waktu. Setiap gelombang datang dan pergi, dan semakin lama, pasir yang dulunya kering dan putih kini semakin surut, tergantikan oleh beton dan tenda-tenda pedagang yang mulai menutupi keindahan alami ini.

Foto: M. Fahrul
Laut ini seperti nenek moyang yang mendendam, tak lagi bisa beristirahat karena ulah manusia yang terus datang, mendekati, memanfaatkan, tetapi tak peduli akan keseimbangan. Lihat saja sekitar sini: tumpukan sampah plastik yang terdampar di bawah kelapa, sisa-sisa styrofoam yang bertebaran seperti serpihan memori. Setiap kali ombak datang, seakan ingin menghapus jejak-jejak itu, tetapi terlalu lelah.
Pemerintah—seperti yang sering saya dengar—berusaha menata Taplau dengan rencana-rencana megah. Dulu, mereka ingin menjadikan pantai ini taman rekreasi modern, penuh dengan fasilitas canggih, menyesuaikan diri dengan gaya hidup cepat yang dipaksakan kota ini. Tapi bukankah itu ironis? Kita ingin membuat Taplau lebih “teratur”, lebih rapi, dengan menutupi segala kekurangannya. Padahal, Taplau yang semrawut ini lah yang justru menyimpan jiwa kota, memelihara ingatan tentang para pendatang pertama yang menatap Samudra Hindia dengan penuh harapan.
Saya pernah membaca cerpen “Si Tua Buta dengan Racun Rindunya” karya Johan Arda yag menceritakan seorang pria tua, tentang bagaimana pantai ini dulunya lebih luas. Ia dulu bisa memancing dengan bebas, menghirup udara yang tak terkontaminasi asap knalpot, dan bermain dengan bebas tanpa takut terganggu oleh tenda-tenda yang menjamur. Tapi sekarang, semua itu memudar. Dengan setiap proyek pembangunan café-café nyentrik yang menjalar dari tepi pantai ke jalan-jalan sempit Kota Padang, Taplau seperti selembar kain yang tersisa sedikit demi sedikit. Pantai ini pun seperti sedang memunggungi kota yang ia cintai, berpaling dari segala keramaian yang tak lagi mengerti cara untuk menghargainya.
Tetapi apakah kita benar-benar peduli? Atau kita hanya menikmati sejenak keindahannya, lalu meninggalkannya dalam kekacauan? Setiap sore, ketika matahari tenggelam dengan kemerahannya yang memikat, saya sering bertanya, apakah nanti pantai ini akan tetap ada untuk mereka yang datang mencari kedamaian, atau apakah ia akan hilang begitu saja, digantikan oleh mall, kafe-kafe Instagramable, atau penginapan berbintang lima yang berjejer dengan rapinya?
Langit perlahan gelap. Para pedagang satu persatu mulai menyalakan lampu gantung warna-warni mereka. Adzan magrib dilantunkan indah oleh muadzin, seakan bernyanyi ke lautan lepas nan tenang.
Para pengamen tetap terus bernyanyi berpindah-pindah dari satu pengunjung ke pengunjung lain. Mereka akan langsung beranjak saat si pengunjung memasukkan selembar uang ke bungkus permen di ujung gitarnya, tanpa repot-repot bernyanyi hingga ending lagu. Mulai dari yang dewasa, remaja, hingga anak-anak. Mulai dari yang menyanyikan lagu lawas Minang, lagu pop barat, hingga anak-anak kecil yang memilih untuk melantunkan ayat-ayat pendek ke telinga para pengunjung yang berpacaran.
Sebelum para pengamen tersebut tiba, saya bergegas berdiri meninggalkan para pengunjung berpasang-pasangan, serta pemandangan yang sudah sepenuhnya gelap. Bukan karena pelit kepada pengamen, tapi adzan magrib menyuruh saya untuk lekas salat.
Jangan pura-pura tuli!
***
Annisa Berliana, mahasiswa semester akhir di Sastra Inggris, Universitas Andalas.
M. Fahrul, senang memotret apa saja, seakan foto adalah cara untuk mengingat sebuah keindahan. Lebih dekat dengannya di instagram @potret.sajak