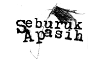Cerita Padang Theater: Buku, Copet, dan Pekerja Seks Pernah Bertemu

Prolog: Rayuan Khas Bandit
Suatu siang yang terik di Pasar Raya Padang pada akhir 2021, sebuah bangunan tua tetap murung, layaknya pertunjukan badai di langit. Suram dan kelabu. Pun dengan anak-anak tangganya.
Bercelana jeans biru yang robek di bagian lutut, serta kemeja bermotif catur, aku meniti tangga tua, akan tetapi karismatik.
Halnya kota di pesisiran, angin laut tetap beredar menembus rambut keriting seleherku. Seolah distorsi gitar berbisik kotor ke telingaku. Bahkan seperti musik alternatif rock asal Seattle (Grunge) yang acap memuat lirik tentang mental, kemiskinan, pengangguran. Seirama dengan tampilan kacauku, begitulah suasana di Padang Theater sepi. Namanya masih sama, walau tak ada lagi bioskop aktif di sana.
Ah! Sampai juga aku di lantai 2 gedung reot menyedihkan ini. Sejenak langkahku melambat, mataku tertegun pada sebuah kios buku. Selemparan batu dari tangga.
Seorang pria paruh baya berkacamata sedikit melorot ke hidung Melayunya, menyadari derap sepatu bootsku sedari tangga. Gerakan tangannya halus meyakinkan –seperti rayuan para mafia–ia menyodorkan sebuah buku tebal bersampul hitam.
Terpampang gambar pria dewasa mengenakan topi fedora dan jas hitam. Ada juga gambar bunga mawar yang seolah dilukis dengan percikan darah. “The Godfather”, judulnya tertulis besar dan berani. Novel kriminal karangan Mario Puzo, penulis asal Italia Selatan.
Hmmm… Sangat Sisilia, sangat Italia. Sangat Minang, sangat Padang. Gayanya yang flamboyan sok paten itu berhasil memprovokasi aku mampir ke kiosnya.
“Dari awal awak mancaliak, lah nampak kalau buku ko nan cocok mah1,” ucapnya sok tahu.
Ya, aku tidak klimis bak mafia Italia di film-film. Parasku lebih menyerupai kartel narkoba asal Kolombia, bahkan kacungnya yang urakan. Tapi bukankah mereka juga kriminal? Outlaw, kata orang Amerika.
Ah! Bisa saja si tua ini merayuku agar beli buku dagangannya. Dia tahu pemuda banal sepertiku haus validasi sebagai pemberontak. Caranya berdagang sangat Italia, sekaligus sangat Minang.
Aku kalah! Buku itu akhirnya kutebus seharga Rp 80.000. Entah mengapa, takdir seperti bermain-main denganku. Beberapa bulan sebelum itu, pada Agustus 2021, aku sempat ngobrol lama dengan seorang bandar sabu-sabu yang menggandrungi novel tentang mafia Italia di Amerika itu.
Sayang sekali, bandar sabu itu sudah pindah kost ke penjara. Meski bukan seorang pemakai, aku selalu menantikan ceritanya yang meletup-letup laksana sensasi memakai ‘garam’ mahal itu.
Begitulah nasib, tidak selalu membawa untung. Begitu juga dengan nasib tempat yang akan aku ceritakan ini: Padang Theater dan Pasar Loak, tempat pekerja seks dan pecinta buku pernah bertemu. Pernah ramai, sekarang sekarat…
***
Naik-Turun Padang Theater dari Kacamata Penjual Buku
“Dulunya di sekitar sini banyak salon, tapi isinya salome (satu lobang rame-rame),” kata Pak Edi sambil ngakak.
Aku nyengir mendengar lelucon khas bapak-bapak itu. Ia adalah salah satu pedagang buku di kawasan Padang Theater yang kutemui kembali pada Kamis, 27 Juli 2024 lalu.
Aku memang tidak lagi menemukan para perempuan pekerja seks di sana. Masa bodo ritual macam itu masih ada atau tidak. Aku trauma pada seorang ibu-ibu 2019 lalu. Saat kulewati sebuah lorong, empat sampai lima orang PSK menawarkan ‘jasanya’. Namun, aku tidak nyaman kala mereka mencoba meraih tanganku, untung saja aku langsung mengibaskan tanganku dan mleangkah lebih cepat. Mereka tersentak dan mundur.
Ketika ditanyai sejak kapan jualan buku, Pak Edi hanya menunjuk plang toko bukunya. Ia sebut plang itu sudah ada sejak akhir 1980-an. Ia termasuk generasi awal berjualan buku di kawasan Padang Theater. Aku hanya tahu satu orang yang jualan lebih dulu daripada Pak Edi, namanya Pak Is, sudah jualan buku di sana dari akhir 1960-an. Namun ia terakhir kali aku temui pada 2021 lalu. Itulah terakhir kali tokonya buka.
Selain mencari nafkah dari penjualan buku, Pak Edi juga menjual bahan-bahan tulisan akademik untuk mahasiswa, terutama yang sedang mengerjakan tugas akhir. Lebih daripada itu, ia pun aktif berdiskusi dengan para pembeli sembari menawarkan bacaan-bacaan yang layak untuk mereka dalami. Edi memang seorang kutu buku dan punya pengalaman sebagai jurnalis. Sehingga aku tidak heran melihat semangatnya yang besar untuk menyebar literasi, jauh melampaui tubuh kecilnya.
Sore itu kawasan pasar loak dan Padang Theater sepi. Walau kata Edi ada 13 toko buku yang masih ada di sana, kebanyakan dari mereka tutup lebih awal. “Ya karena sepi juga, mungkin mereka malas buka toko lama-lama,” ungkap Edy. Selain kiosnya, kulihat hanya 3 toko buku lain yang masih buka.
Berbeda dari era 1970 hingga awal 2000-an silam, ketika masih Padang Theater masih ramai dengan pedagang dan pengunjung. Wajar saja, saat itu masih ada bioskop, wahana game arcade (semacam dingdong), pedagang burung dan segala jenis binatang, dan bahan-bahan tekstil. Meskipun, beberapa penjahit masih bebal bertahan.
Aku pernah dengar bahwa di kawasan ini banyak copet. Menanggapi itu, Edi tertawa.
“Dulu copet justru kaburnya ke sini. Dompet dan tas curian pun mereka bawa ke sini,” ucapnya mengenang masa-masa ‘kejayaan’ Padang Theater.
Menurut Edi, Padang Theater perlahan-lahan menjadi sepi karena banyak faktor selama bertahun-tahun. Mulai dari resesi ekonomi, kios pakaian dan tekstil yang sudah banyak menjamur di luar, hingga keberadaan internet dan smartphone. Yang pasti, bagi pedagang buku seperti Edi mudahnya mendapat sumber bacaan online adalah salah satu alasan kenapa mereka kini jadi jarang dilirik.
Sebagai pedagang buku yang sudah pernah melewati masa orde baru, ia tentu tahu soal pemberedelan maupun razia buku. Beruntung, ia tidak pernah kena. Walau ia sempat mengeluarkan buku-buku yang sempat ditarik dari peredaran, salah satunya yang membahas dugaan-dugaan di balik G30S dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Pas orang lagi periksa-periksa buku, kebetulan saya lagi tidak buka toko,” katanya sambil nyengir mengenang nasib mujurnya. Ia ingat, pada sekitar reformasi 1998 ada ormas-ormas yang turun untuk memeriksa buku dan bacaan yang beredar dan dianggap tidak patut. Ormas yang bergerak itu ada yang berlabel keagamaan, ada juga yang memakai baret dan pakaian loreng-loreng.
“Tapi mereka tidak bertindak kasar. Cuma periksa buku-buku, dan mengambil yang dianggap tidak layak.” Aku tidak tahu apa yang Edi maksud dengan ‘bertindak kasar’. Bukankah pembungkaman itu sendiri juga merupakan bentuk kekerasan? Ah ntahlah.
Dari toko buku milik Edi, kubeli buku “Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari’ati” karya Eko Supriyadi. Sebelumnya ia menawarkan buku-buku tentang politik dan ekonomi Amerika, tapi kutolak karena belum terlu tertarik. “Caliaklah dulu, ka sinan kiblat pemerintah awak beko ma2,” katanya berargumen.
Aku kemudian bergeser ke toko buku milik Tommy. Ia lebih banyak menjual majalah-majalah lama dan komik-komik bekas. Aku sudah tiga kali mampir dan ngobrol di tokonya.
Pertama kali pada 2022 silam, bulan Mei yang bertepatan bulan Ramadhan. Sore hari itu, aku adalah penglarisnya. Mungkin juga yang terakhir untuk hari itu. Aku membeli salah satu seri komik Tintin–karakter reporter fiktif asal Belgia. Saat itu, Tommy bahkan mengaku sering menjual rugi buku-buku yang ia punya.
Namun pada Agustus 2023, aku mendatanginya lagi dan mendapat kabar gembira. “Sekarang komik-komik Jepang banyak laku dijual online,” ungkapnya lega. Namun aku yang sial kala itu. Aku sebenarnya hendak mencari majalah National Geographic yang membahas kawasan Gayo, Aceh. Sayang, majalah-majalah itu sudah diborong oleh sebuah toko aksesoris. Ternyata bacaan itu bukan untuk dipajang lalu dibaca, namun dipotong-potong untuk jadi hiasan.
Pada Juli 2024 ini, Tommy menunjukkan tumpukkan majalah sastra Horison kepadaku. Ada sepuluh edisi, salah satunya edisi Oktober 2003. Majalah itu sendiri terakhir terbit pada 2016.
“Majalah Horison saya banyak yang ndak laku,” katanya.
“Sudah abang coba tawarkan ke mahasiswa-mahasiswa sastra, atau jual online?” tanyaku.
Upaya itu sudah ia lakukan, namun hasilnya nihil. Aku tertarik dengan majalah itu, tapi majalah Tempo Edisi Khusus Soekarno terbitan tahun 2001 lebih sexy. Majalah itu sebenarnya pesanan seseorang, akan tetapi si calon pembeli tidak jadi datang hingga berbulan-bulan.
***
Epilog: Kenapa Pasar Buku Bekas serta ‘Kekumuhannya’ Masih Ada?
Selain di Padang Theater, aku lebih dulu merasakan sensasi cari-cari buku bekas di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Aku bahagia bisa bercengkrama dengan mereka. Umumnya, mereka berwawasan luas dan pintar, namun juga asyik dan tidak kaku. Oh iya, Senen juga lama dikenal dengan keberadaan copet dan pekerja seks.
Walau tidak mendapatkan buku yang kucari, aku sudah cukup senang ketika mengetahui buku itu pernah ada di sebuah toko walau pada akhirnya ia ‘jadian’ dengan orang lain.
“Heavier Than Heaven, biografi Kurt Cobain itu ya? Wah udah dibeli orang kemarin, fan Nirvana juga dia,” kata pedagang buku di Pasar Senen padaku. Di satu sisi aku senang mendengar kabar orang sejenisku berhasil memuaskan minatnya. Sayang sekali kita tidak bertemu dan saling mengenal.
Gawai bisa saja semakin canggih, bahan bacaan online semakin beredar luas, namun tidak akan ada yang bisa menggantikan pengalaman otentik berkeliling toko buku, berbincang dengan pedagangnya, lalu membawa pulang sebuah buku dengan kertas kasar beraroma tua.
Di Senen atau di Padang Theater, belum pernah juga kudengar pedagang-pedagang buku mengutuk para pencopet atau para pekerja seks dengan tarif murah itu. Sebagian mereka mungkin menyindir, tapi aku masih merasakan simpati sebagai sesama manusia. Sebagai sesama orang yang menjadi korban dalam sistem ekonomi kapitalis ini. Namun secara mental, aku tahu mereka bukan orang-orang yang kalah.
Padang Theater masih begitu saja. Suram dan sepi. Sementara sebuah toko buku besar yang menjual buku yang lebih mahal terus berdiri dan merayu pengunjung. Di antara buku-buku di toko dengan ruangan ber-AC itu, beberapa penulis mungkin masih hidup sederhana. Apa lagi hasil penjualan buku harus dipotong pajak yang tidak sedikit.
Bentuk prostitusi modern pun semakin beragam bentuknya. Sementara para perempuan pekerja seks di Padang Theater mungkin belum punya cukup uang untuk punya smartphone dan memanfaatkan aplikasi Mi-Chat, atau semacamnya. Oh iya, lagi pula mereka sudah terlalu tua dan mungkin tidak sesuai selera pasar. Siapa juga yang peduli kalau di antara mereka mungkin adalah janda dan punya anak tiga?
Mereka dan buku, sama-sama saling bertahan.
- “Dari awal pandangan, saya sudah tahu buku ini yang cocok untukmu.”
- “Lihat saja, arah pemerintah kita nanti ke sana.”
Daffa Benny, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Andalas.